Abstrak
Penelitian ini mengkaji Kidung Sundayana dan Perang Bubat dalam kerangka politik identitas, dengan fokus pada bagaimana konflik antara Majapahit dan Pajajaran membentuk konstruksi identitas etnis Jawa dan Sunda di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan teori politik identitas Lukmantoro, penelitian ini menemukan bahwa Perang Bubat tidak hanya mencerminkan konflik kekuasaan antar kerajaan, tetapi juga menjadi simbol resistensi Sunda terhadap dominasi Jawa. Narasi sejarah tersebut menciptakan segregasi sosial-politik yang diwariskan hingga masa kini, terlihat dari mitos larangan pernikahan Jawa–Sunda dan persepsi dominasi etnik Jawa dalam kepemimpinan nasional. Politik identitas yang dimainkan oleh Gajah Mada mengubah relasi diplomatik menjadi konflik berdarah, yang kemudian membentuk memori kolektif masyarakat dan memengaruhi dinamika politik modern Indonesia. Dengan demikian, Kidung Sundayana tidak hanya menyimpan nilai sastra, tetapi juga menjadi refleksi historis atas peran identitas etnis dalam membentuk relasi kekuasaan dan struktur sosial-politik di Nusantara.
Kata kunci: Kidung Sundayana; Perang Bubat; politik identitas; Jawa–Sunda; sejarah politik
Latar Belakang
Indonesia memiliki beragam kearifan lokal dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat yang masih mempercayainya, sebagai contoh manuskrip kuno Kidung Sundayana. Manuskrip tersebut menjadi salah satu sumber pustaka yang menjelaskan Perang Bubat dan menyisakan luka bagi hubungan kerajaan besar di Majapahit dan Pajajaran. Kidung Sundayana menceritakan adanya rencana pernikahan yang dilakukan Hayam Wuruk dari Majapahit dengan Dyah Pitaloka dari Pajajaran dengan mengutamakan rasa kasih sayang dibandingkan kepentingan politik. Namun, Gajah Mada melihat rencana tersebut sebagai strategi politik.
Melalui pandangan politik Gajah Mada, kedatangan putri Sunda merupakan tanda takluknya terhadap Majapahit. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Gajah Mada dengan menjadikan Dyah Pitaloka sebagai upeti, namun hal tersebut ditolak dengan mengangkat senjata karena dianggap menjatuhkan martabat Sunda. Penolakan tersebut dilakukan oleh Prabu Linggabuana sebagai ksatria Sunda. Dalam waktu yang singkat, Gajah Mada memerintahkan laskar Majapahit untuk bertempur dengan menggunakan pakaian perang lengkap. Kondisi tersebut dihadapi oleh Sang Prabu Maharaja dengan menolak permintaan Majapahit dan mengucapkan:
“Walaupun darah akan mengalir bagaikan sungai di palagan Bubat ini, kehormatanku dan semua ksatria Sunda tidak akan membiarkan pengkhianatan terhadap negara dan rakyatku, karena itu janganlah kalian bimbang” (Sondarika et al., 2024).
Sehingga terjadilah perang tak seimbang antara pasukan Gajah Mada dan Raja Sunda pada hari Selasa Wage, tanggal 4 September 1357, yang mengakibatkan gugurnya Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka memilih mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini tidak hanya berakhir sebagai tragedi sejarah, tetapi juga meninggalkan warisan ideologi yang berakar kuat dalam politik identitas di Indonesia. Narasi ini membentuk persepsi historis bahwa dominasi politik di tingkat nasional cenderung didominasi oleh kelompok etnis tertentu, khususnya Jawa, sementara kelompok lain seperti Sunda mengalami marginalisasi simbolik.
Bahkan hingga kini, mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda masih hidup dalam masyarakat, menunjukkan bahwa warisan politik identitas masa lampau tetap memengaruhi dinamika sosial budaya kontemporer. Oleh karena itu, kajian terhadap Kidung Sundayana menjadi penting bukan hanya sebagai studi sastra atau sejarah, melainkan juga sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana konstruksi identitas etnis terbentuk, dipertahankan, dan diwariskan dari masa ke masa.
Pembahasan
1. Politik Identitas dalam Kidung Sundayana
Kidung Sundayana mengisahkan rencana pernikahan antara Hayam Wuruk, raja Majapahit, dengan Dyah Pitaloka, putri dari Kerajaan Pajajaran, yang pada awalnya dilandasi oleh semangat diplomasi dan kasih sayang. Hayam Wuruk menginginkan pernikahan ini sebagai bentuk aliansi politik yang harmonis, dengan harapan dapat memperkuat hubungan antara dua kerajaan besar di Nusantara. Namun, di balik niat baik tersebut, Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit memiliki agenda politik tersendiri yang jauh lebih ambisius. Ia memandang kedatangan rombongan Sunda sebagai simbol penaklukan, bukan sebagai upaya mempererat persaudaraan antaretnis. Dalam pandangan Gajah Mada, Dyah Pitaloka tidak lebih dari sekadar upeti yang menandakan tunduknya Pajajaran kepada kekuasaan Majapahit (Sondarika et al., 2024).
Penolakan keras terhadap perlakuan ini datang dari Prabu Linggabuana, raja Pajajaran, yang merasa martabat dan kehormatan bangsanya telah diinjak-injak. Prabu Linggabuana dengan tegas menolak permintaan Majapahit yang menganggap putrinya sebagai tanda takluk, dan memilih untuk mengangkat senjata demi menjaga harga diri kerajaannya. Sikap ksatria ini memicu perang besar di Bubat, di mana pasukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada menyerang rombongan Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pertempuran yang tidak seimbang tersebut berakhir tragis dengan gugurnya Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka yang memilih bunuh diri demi menjaga kehormatan keluarganya. Kisah ini kemudian menjadi simbol resistensi Sunda terhadap dominasi Jawa, sekaligus menandai awal dari segregasi identitas yang semakin tajam di antara kedua etnik tersebut (Sondarika et al., 2024).
Majapahit, sebagai representasi etnik Jawa, secara sadar menggunakan strategi politik identitas untuk menegaskan superioritas dan kekuasaan atas Sunda. Gajah Mada memanfaatkan posisi Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara untuk menuntut pengakuan dari kerajaan lain, termasuk Pajajaran. Ia tidak hanya ingin memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga ingin menegaskan bahwa identitas Jawa memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan etnik lain. Dalam proses ini, Gajah Mada menuntut penaklukan simbolik dari Sunda, yang diwujudkan melalui permintaan agar Dyah Pitaloka dijadikan upeti. Tindakan ini jelas memperlihatkan bagaimana politik identitas bekerja dalam membangun hierarki sosial dan politik di antara kelompok etnis (Haryono, 2019).
Di sisi lain, Pajajaran yang diwakili oleh Prabu Linggabuana dan para ksatrianya berusaha keras mempertahankan kehormatan serta identitas etnis mereka. Mereka menolak tunduk pada simbolisasi kekalahan yang dipaksakan oleh Majapahit, meskipun harus menghadapi risiko kehilangan nyawa dan kehancuran kerajaan. Sikap ini menunjukkan bahwa identitas etnis Sunda tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menentukan sikap politik dan sosial mereka. Konflik ini mempertegas batas identitas antara Jawa dan Sunda, sekaligus memperdalam sentimen “kami” (Sunda) versus “mereka” (Jawa) yang terus diwariskan dari generasi ke generasi (Haryono, 2019).
Peristiwa Perang Bubat akhirnya memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh politik identitas dalam membentuk dinamika kekuasaan dan relasi antaretnis di Nusantara. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara Majapahit dan Pajajaran, tetapi juga melahirkan narasi dan mitos yang memperkuat segregasi identitas di masa berikutnya. Politik identitas yang dimainkan oleh Gajah Mada telah menciptakan luka sejarah yang sulit disembuhkan, sekaligus menjadi pengingat bahwa perebutan kekuasaan sering kali mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Sampai hari ini, masyarakat masih merasakan dampak dari politik identitas yang diwariskan oleh peristiwa tragis tersebut (Sondarika et al., 2024).
2. Dampak Politik Identitas terhadap Hubungan Diplomatik
Politik identitas yang dimainkan dalam Perang Bubat telah merusak tatanan diplomasi yang seharusnya menjadi jembatan perdamaian antara Majapahit dan Pajajaran. Alih-alih memperkuat hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, kedua kerajaan justru terjebak dalam konflik yang dipicu oleh kepentingan politik dan penegasan identitas etnis. Gajah Mada lebih mengutamakan motif politik daripada nilai-nilai kekeluargaan, sehingga diplomasi yang telah dibangun runtuh seketika di medan perang Bubat. Keputusan untuk memaksakan kehendak atas dasar identitas etnis telah menutup ruang kompromi dan dialog, sehingga konflik menjadi tak terhindarkan. Akibatnya, kedua belah pihak kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa politik identitas dapat menghancurkan tatanan sosial dan diplomasi yang telah susah payah dibangun (Haryono, 2019).
Dampak dari politik identitas yang mengakar dalam Perang Bubat tidak hanya dirasakan pada masa itu, tetapi juga berlanjut hingga generasi berikutnya. Luka sejarah yang ditinggalkan oleh konflik ini melahirkan berbagai mitos dan stigma, seperti larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda, yang masih dipercayai sebagian masyarakat hingga saat ini (Afnan, 2022). Mitos tersebut menjadi simbol segregasi identitas yang memperkuat batas-batas sosial antara kedua etnik, sehingga mempersempit ruang interaksi dan kolaborasi di berbagai bidang. Selain itu, peristiwa ini juga membentuk persepsi bahwa etnik Jawa memiliki dominasi dalam politik nasional, sedangkan etnik Sunda cenderung tersisih dari posisi puncak kepemimpinan. Segregasi identitas yang diwariskan dari Perang Bubat telah menciptakan tantangan tersendiri dalam membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan harmonis (Sondarika et al., 2024).
Kisah Perang Bubat dalam Kidung Sundayana menjadi pengingat penting betapa destruktifnya politik identitas dalam sejarah Nusantara. Konflik antara Majapahit dan Pajajaran tidak hanya menorehkan luka mendalam bagi kedua belah pihak, tetapi juga membentuk pola interaksi dan persepsi yang masih terasa hingga hari ini. Politik identitas yang dimainkan oleh Gajah Mada dan Prabu Linggabuana telah mempertegas batas-batas etnis, memperdalam segregasi, serta melahirkan mitos dan stigma yang membatasi ruang interaksi antar etnis. Dampak dari peristiwa ini masih membayangi kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks representasi dan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu belajar dari sejarah dan berupaya membangun relasi yang lebih inklusif, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan di atas kepentingan identitas kelompok. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih harmonis dan berkeadilan.
3. Kaitan Fenomena Sejarah Kidung Sundayana dengan Politik Indonesia Saat Ini
Sejarah panjang bangsa Indonesia tidak hanya berisi kisah kejayaan dan harmoni, tetapi juga menyimpan luka-luka lama yang masih membekas dalam memori kolektif masyarakat. Salah satu peristiwa yang hingga kini masih membayang-bayangi relasi antar etnis di Indonesia adalah Perang Bubat yang terekam dalam Kidung Sundayana. Kisah tragis ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap politik dan identitas etnis di tanah air. Narasi sejarah Perang Bubat yang mengisahkan konflik antara Majapahit dan Pajajaran telah membentuk persepsi kuat tentang dominasi politik etnis Jawa di Indonesia hingga masa kini. Mitos yang berkembang dari peristiwa tersebut memperkuat keyakinan bahwa kekuasaan nasional, terutama posisi strategis seperti Presiden Republik Indonesia, hampir selalu dipegang oleh tokoh berdarah Jawa, sementara etnis Sunda jarang sekali mencapai puncak kepemimpinan tersebut. Sebagai contoh, mantan Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Abdurrahman Wahid, dan Joko Widodo keseluruhannya berasal dari Jawa. Konstruksi politik identitas yang lahir dari sejarah ini membuktikan bahwa memori kolektif dan trauma masa lalu masih sangat berpengaruh dalam sistem politik modern Indonesia, bahkan menjadi salah satu faktor yang membentuk pola kepemimpinan dan distribusi kekuasaan di tingkat nasional.
Mitos ini merupakan bentuk pertahanan identitas dan upaya menjaga kehormatan kelompok yang pernah mengalami trauma sejarah, sehingga interaksi sosial-politik antara kedua etnis masih dibayangi oleh ingatan kolektif akan konflik masa lalu. Politik identitas masih menjadi alat utama dalam mobilisasi dan segmentasi kekuasaan di Indonesia, terutama dalam kontestasi pemilu dan perebutan jabatan publik (Haryono, 2019). Isu representasi etnis dalam politik nasional pun kerap memunculkan sentimen primordial yang berakar pada narasi sejarah seperti Perang Bubat, sehingga relasi antar etnis di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Dapat kita ketahui bahwa sejarah Perang Bubat tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga turut membentuk dinamika politik dan sosial di Indonesia hingga hari ini. Fenomena politik identitas yang berakar dari sejarah Perang Bubat mengajarkan kita bahwa luka lama yang tidak disembuhkan akan terus memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penting bagi generasi sekarang untuk memahami sejarah secara kritis, tidak sekadar sebagai narasi, tetapi sebagai pelajaran berharga agar politik identitas tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk membangun persatuan dan keadilan sosial di Indonesia.
Analisis Teori Politik Identitas
Politik identitas menjadi salah satu aspek penting dalam memahami dinamika konflik dan relasi antar etnis di Indonesia, terutama jika kita menelusuri akar sejarahnya melalui kisah Perang Bubat yang terekam dalam Kidung Sundayana. Analisis teori politik identitas menawarkan perspektif kritis untuk melihat bagaimana narasi sejarah membentuk batas-batas sosial, memperkuat stereotip, dan memengaruhi perilaku politik masyarakat hingga saat ini. Lukmantoro, sebagaimana dikutip dalam Nasrudin (2018), menyatakan bahwa politik identitas merupakan strategi kelompok yang didasarkan pada kesamaan identitas, seperti ras atau etnis, untuk mengedepankan kepentingan kelompoknya.
Jika kita mengaitkan teori ini dengan konteks Kidung Sundayana, terlihat jelas bahwa baik Majapahit yang beridentitas Jawa maupun Pajajaran yang beridentitas Sunda sama-sama menggunakan identitas etnis sebagai landasan utama dalam bertindak dan berkonflik. Gajah Mada, melalui strategi politiknya, memanfaatkan identitas Jawa untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Majapahit dan memperluas hegemoni dengan menuntut penaklukan simbolik terhadap Sunda. Sementara itu, Pajajaran menolak keras subordinasi identitas tersebut dan memilih mempertahankan martabat serta otonomi etnisnya, meskipun harus mengorbankan nyawa dan kehormatan.
Konflik ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya merusak diplomasi dan hubungan antar kerajaan, tetapi juga memperdalam segregasi sosial yang dampaknya terasa hingga masa kini (Sondarika et al., 2024). Dalam konteks Indonesia modern, politik identitas tetap menjadi instrumen penting dalam perebutan kekuasaan, pembentukan koalisi, dan penentuan kebijakan publik. Konstruksi identitas etnis yang diwariskan dari sejarah, seperti Perang Bubat, terus memengaruhi pola kepemimpinan, distribusi kekuasaan, hingga munculnya mitos sosial seperti larangan pernikahan Jawa–Sunda yang masih dipercaya sebagian masyarakat (Afnan, 2022). Dengan demikian, teori politik identitas sangat relevan untuk memahami mengapa narasi sejarah dan mitos etnis tetap kuat membentuk perilaku politik masyarakat Indonesia, serta menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun relasi antar etnis yang lebih harmonis dan inklusif (Haryono, 2019).
Melalui lensa teori politik identitas, kita dapat melihat bahwa konflik dan narasi sejarah seperti Perang Bubat tidak sekadar menjadi bagian dari masa lalu, melainkan terus hidup dan memengaruhi struktur sosial-politik Indonesia hingga kini. Oleh sebab itu, refleksi kritis terhadap sejarah dan upaya membangun kesadaran kolektif menjadi sangat penting agar politik identitas tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa.
Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa Kidung Sundayana dan peristiwa Perang Bubat bukan sekadar kisah sejarah masa lalu, melainkan refleksi nyata dari praktik politik identitas yang telah membentuk konstruksi etnisitas dan dinamika kekuasaan di Indonesia hingga saat ini. Melalui analisis naratif dan pendekatan teori politik identitas Lukmantoro, konflik antara Majapahit dan Pajajaran ditafsirkan sebagai simbol resistensi Sunda terhadap dominasi kekuasaan etnis Jawa. Politik identitas yang dimainkan oleh Gajah Mada dalam konteks penaklukan simbolik telah menciptakan luka sejarah yang memperdalam segregasi sosial dan menumbuhkan mitos, seperti larangan pernikahan Jawa–Sunda serta persepsi dominasi etnik Jawa dalam kepemimpinan nasional.
Narasi dalam Kidung Sundayana memperlihatkan bagaimana memori kolektif dan trauma etnis dapat diwariskan lintas generasi, memengaruhi hubungan diplomatik, interaksi sosial, dan representasi politik di era modern. Politik identitas tidak hanya berperan dalam menciptakan batas-batas antar kelompok etnis, tetapi juga menjadi instrumen perebutan kekuasaan yang membentuk struktur sosial-politik Indonesia hingga kini. Oleh karena itu, memahami dan merefleksikan sejarah Perang Bubat secara kritis menjadi penting untuk mendorong rekonsiliasi kultural dan membangun relasi antar etnis yang lebih inklusif, adil, dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Daftar Referensi
- Afnan, D. (2022). Mitos larangan menikah antara orang Jawa dengan orang Sunda dalam perspektif masyarakat modern. Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal, 2(1), 157–176. https://doi.org/10.21009/Arif.021.10
- Haryono, H. (2019). Identity politics and symbolic interactions between Sundanese and Javanese in Indonesia. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 1(1), 49–56. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i1.7
- Nasrudin, J. (2018). Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018–2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1), 34–47.
- Sondarika, W., Ratih, D., & Herdianto, H. (2024). Dampak Perang Bubat terhadap identitas dan kebudayaan masyarakat Sunda. Jurnal Artefak, 11(2), 215–228. https://doi.org/10.25157/ja.v11i2.16397
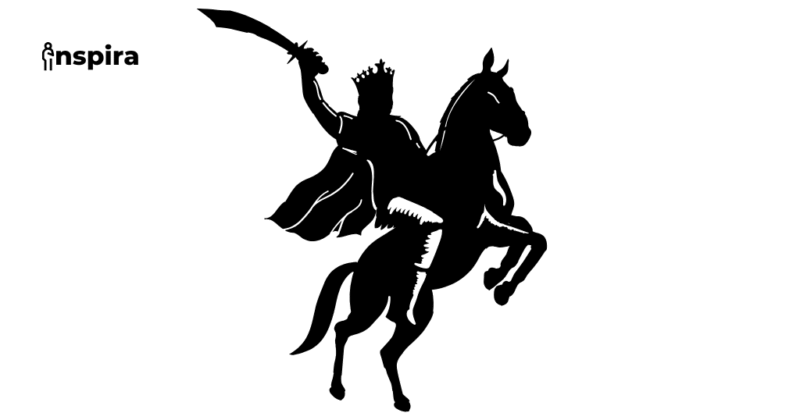
1 comment
Terima kasih. Analisis yang cukup gamblang dan relevan dengan kondisi kekinian, terutama dalam bidang politik. Terus berkarya, Mas.