Prawacana
Sesuai dengan pengalaman subyektif penulis semasa menjadi siswa, bahkan mahasiswa, guru atau dosen akan mengomunikasikan tema ketika menugasi mahasiswa/siswa untuk menulis. Misalnya, “Tulislah puisi dengan tema keindahan alam”, “Tulislah pengalaman ketika berlibur”, atau “Buatlah karangan dengan tema kenakalan remaja”. Dari sudut pandang kajian semantik dan psikologi belajar, pemberian tema untuk memantik aktivitas berbahasa produktif (berbicara, menulis, dan menyaji) seperti itu sudah tidak tepat.
Untuk mendukung rasional sederhana tersebut, dalam artikel ini dibahas tiga subtopik utama. Ketiga subtopik itu adalah: (1) konsep sederhana tentang semantik dan berpikir, (2) urgensi penyajian konteks sesuai dengan konsep dasar semantik dan psikologi belajar, dan (3) contoh-contoh konteks dan pemanfaatannya untuk memantik pemroduksian teks nonfaktual. Teks-teks nonfaktual adalah teks-teks subgenre opini, cerita, puitis, dan drama. Sementara teks-teks faktual adalah variasi teks laporan hasil observasi (LHO), berita, eksplanasi, biografi, prosedur, dan eksplanasi. Konteks, seperti yang akan dicontohkan dan dipaparkan pemanfaatannya, tidak tepat untuk memantik aktivitas memproduksi teks-teks faktual. Permasalahan pemanfaatan konteks untuk memproduksi teks-teks faktual akan dibahas pada artikel lain.
Konsep Sederhana tentang Konteks, Semantik, dan Berpikir
Foote (2023) menyatakan bahwa peneruka telaah tentang semantik modern adalah Michel Breal, seorang filolog Perancis. Istilah semantics pertama kali digunakan pada 1883. Sesuai dengan bidang keilmuannya, Breal mengkaji bagaimana bahasa-bahasa diorganisasikan, bagaimana perubahan bahasa sesuai dengan perkembangan waktu, serta koneksi-koneksi interbahasa itu sendiri (misalnya keterkaitan antara satu kata dengan kata lainnya dalam satu frasa, antara satu frasa dengan frasa lainnya dalam satu klausa dan kalimat). Singkatnya, semantik adalah telaah tentang bahasa dan relasi maknanya.
Cikal-bakal telaah semantik sebenarnya sudah lama. Plato, seorang filsuf Yunani (429-347 SM) dalam karyanya, Cratylus mengisyaratkan tentang pentingnya makna. Thomas (2012) yang mengkritisi buku The Cratylus of Plato: A Commentary yang ditulis oleh Francesco Ademollo (2011) bahwa Plato meyakini bahwa nada dalam bahasa (jeda, tekanan, dan intonasi) itu sudah memiliki makna. Selain itu, Plato menyajikan perdebatan tentang makna kata: apakah harus sesuai dengan bentuk yang mewakili pada satu sisi dan makna kata itu tergantung pada konvensi atau kesepakatan. Salah satu butir yang diperdebatkan itu merupakan cikal-bakal lahir dan berkembangnya etimologi.
Semantik berkaitan dengan makna. Sementara itu, makna adalah hasil olah pikir manusia. Oleh sebab itu, pemaknaan atas suatu tuturan (dapat berupa kata, frasa, klausa, kalimat atau lebih dari itu, tataran wacana) itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan bahasa namun juga terkait dengan aspek-aspek nonbahasa. Hal itu dinyatakan oleh Expert.ai. Team (2022) bahwa semantik adalah studi tentang makna kata dan kalimat yang juga memperhitungkan hubungan bentuk linguistik dengan konsep nonlinguistik dan representasi mental untuk menjelaskan bagaimana kalimat atau tuturan itu dipahami. Jadi, terdapat keterkaitan antara bahasa dalam konteks semantik dengan pikiran.
Keterkaitan antara berbahasa dan berpikir memicu perdebatan klasik: manakah terlebih dahulu diupayakan oleh individu, berbahasa ataukah berpikir? Tentu saja, ketika pertanyaan ini dilontarkan ke publik, jawaban tercepat yang muncul adalah, “Berpikir mendahului berbahasa!” Namun ketika dicontohkan, misalnya “5 x 5 = 25”, bukankah mengoperasikan lima, kali, lima, sama dengan dan dua puluh lima itu otak manusia menggunakan bahasa? Publik pun meragukan jawaban bahwa berpikir mendahului berbahasa.
Penjelasan paling lugas tentang keterkaitan berpikir dan berbahasa dapat ditemukan dalam Language & Thought/Overview & Relationship (study.com, 2024). Menurut sumber ini, cara berpikir seseorang berkorelasi langsung dengan bahasanya. Pikiran adalah proses kognitif yang memungkinkan individu membuat hubungan dan memahami dunia di sekitarnya. Bahasa, sebagai piranti berkomunikasi komunikasi, memungkinkan individu untuk mengekspresikan dan menafsirkan pikiran dan idenya. Tegasnya, bahasa merupakan sarana untuk berpikir.
Berkaitan dengan pemberian tema ketika menugasi menulis kepada mahasiswa/siswa, berarti pemberian ide. Ide yang diungkapkan dalam “Tulislah puisi dengan tema keindahan”, tentunya hanya satu kata yang tidak dipahami dengan baik karena tulislah itu jelas, puisi juga jelas, dengan tema juga jelas. Satu kata yang tidak jelas adalah keindahan. Sebab, pemaknaan individu atas keindahan sangat variatif: kasih sayang orang tua itu keindahan, pemandangan alam, juga keindahan, menikmati musik atau lagu juga keindahan, bersenda-gurau dengan rekan-rekan juga keindahan, dan serentetan kemungkinan hal lain yang dimaknai sebagai keindahan. Intinya, semakin pendek kata (dalam hal ini tema) akan semakin tidak jelas maknanya dan mengundang multitafsir.
Penafsiran mahasiswa/siswa akan semakin spesifik jika tema dielaborasi. Misalnya, tentang keindahan tadi dielaborasi menjadi “Tulislah puisi dengan tema keindahan pantai Padang pada waktu senja.” Pernyataan itu semakin spesifik dan jelas karena dosen/guru dapat memastikan bahwa mahasiswa/siswa mengetahui persis pantai Padang dan berkemungkinan besar pernah menikmati keindahan pantai tersebut pada waktu senja. Meskipun demikian, kemungkinan multitafsir masih tetap ada. Misalnya, ada mahasiswa/siswa yang menikmati keindahan pantai Padang pada waktu senja namun seorang diri, ada yang sedang saat itu berduka, ada yang menikmati ramai-ramai dengan rekan-rekan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perluasan tema hendaknya lebih komprehensif, yaitu melalui pemberian atau penyajian konteks.
Urgensi Penyajian Konteks sesuai dengan Konsep Dasar Semantik dan Psikologi Belajar
Istilah konteks merupakan istilah yang multitafsir dan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Lebih dari itu, Airenti dan Plebe (2017) menyatakan bahwa pemaknaan tentang konteks itu dapat bersifat kontroversial. Dalam ilmu sosial, misalnya, konteks adalah seluruh unsur yang memengaruhi sosok sosial seperti tempat, keberadaan benda hidup, benda mati, manusia, nilai-nilai, dan sebagainya. Dalam sejarah, konteks terkait dengan waktu, tempat, pelaku, dan peristiwa. Sesuai dengan judul, konteks dalam artikel ini dikaitkan dengan komunikasi terbatas, yaitu komunikasi dosen/guru dan mahasiswa/siswa dalam pemberian tugas menulis atau memproduksi teks.
Pemberian atau pengajuan tema, seperti telah dibahas sebelumnya, sebenarnya juga pemberian konteks. Namun, sesuai dengan kaidah semantik: semakin pendek tuturan akan semakin multitafsir. Oleh sebab itu, tema hendaknya diperluas sehingga menjadi sebuah konteks yang layak. Tentu saja, ukuran layak dan tidaknya, salah satunya, tergantung pada audiens (dalam hal ini adalah siswa atau mahasiswa). Untuk itu, pembahasan tentang konteks dalam artikel ini dibatasi pada audiens siswa sekolah menengah dan mahasiswa.
Pemberian konteks yang layak itu juga relevan dengan teori psikologi belajar kognitif dan konstruktivistik. Dalam pandangan penganjur psikologi konstruktivistik, belajar adalah merekonstruksi pengetahuan. Rekonstruksi akan berlangsung bukan dari butiran-butiran realitas tetapi realitas yang utuh. Jadi, individu akan mencermati realitas yang utuh, mempreteli atau mendekonstruksi realitas tersebut, merekonstruksi, dan akhirnya mengkonstruksi pengetahuannya. Proses ini bersifat dinamis, berlangsung seumur hidup selama individu memiliki kesehatan berpikir. Misalnya, ketika mencermati pohon, hal pertama yang dicermati adalah pohon secara utuh barulah dipreteli (dekonstruksi) bahwa pohon itu terdiri atas batang, dahan, ranting, daun, bunga atau buah, serta akar. Setelah itu, individu akan merekonstruksikan kembali secara kognitif tentang pohon tersebut sehingga tertanamlah konstruksi yang baru berkaitan dengan konsep pohon. Konsep ini juga sejalan dengan pendapat McLeod (2024),
“Constructivism is a learning theory that emphasizes the active role of learners in building their own understanding”.
Jadi, meskipun proses belajar-mengajar (PBM), misalnya berlangsung dalam kelas yang terdiri atas beberapa orang mahasiswa/siswa, namun proses belajar itu sendiri berlangsung dalam sistem kognisi individu (mahasiswa/siswa) itu sendiri.
Berdasarkan deskripsi singkat tentang keterkaitan pemberian konteks dengan semantik dan psikologi belajar, diperoleh gambaran bahwa konteks itu penting untuk memantik individu memproduksi teks, termasuk menulis, berbicara, atau menyaji. Konteks menyajikan gambaran utuh, berbeda dengan tema yang memicu gambaran terlalu umum. Selain itu, ada empat manfaat pemakaian konteks. Pertama, konteks yang layak akan memicu kepedulian/kesadaran mahasiswa/siswa tentang adanya suatu masalah di sekitar hidup dan kehidupannya. Kedua, akan membantu mahasiswa/siswa memahami apa keinginan pemberi konteks (dosen/guru). Ketiga, konteks yang layak akan memicu mahasiswa/siswa merekonstruksi dan mengonstruksi pengetahuannya. Keempat, konteks yang layak membantu mahasiswa/siswa mengelola sistem kognisinya untuk mengerjakan tugas secara bertahap: mencermati, memahami, menyusun rancangan atau kerangka, mengembangkan menjadi draf, dan merevisi.
Contoh-Contoh Konteks dan Pemanfaatannya
Untuk memberikan gambaran tentang konteks sebagai pengganti tema sebagai pemicu aktivitas mahasiswa/siswa memproduksi teks, berikut ini disajikan dua contoh konteks.
Konteks 1: Potret Buram Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup, termasuk manusia. Tanpa lingkungan hidup yang layak, manusia juga tidak akan mampu hidup dengan layak. Berbeda dengan makhluk lain, keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidupnya malahan bersifat timbal-balik. Manusia memerlukan lingkungan hidup dan lingkungan hidup memerlukan campur tangan manusia agar terpelihara, bahkan dapat dieksploitasi bagi kehidupan serta kemaslahatan manusia. Lebih dari itu, manusia dan lingkungan hidup itu sama-sama merupakan makhluk ciptaan Sang Khalik.
Sangat disayangkan, fenomena manusia menyia-nyiakan lingkungan hidup dapat kita jumpai di mana-mana, khususnya di Indonesia. Cermati saja lingkungan sekitar kita, sungai, pantai, laut, danau, hutan, pasar, dan sebagainya. Ungkapan bijak-bestari “Kebersihan itu adalah sebagian dari iman” terkesan hanya gaung di rumah-rumah peribadatan, sebatas spanduk, belum merasuk ke dalam kehidupan manusia, ke dalam rasa, karsa, dan cipta. Kecemaran, kerusakan, dan ketidakbersihan lingkungan sekitar kita semakin merajalela. Logika sederhananya, jika lingkungan hidup rusak, tidak sehat, tentu manusia-manusia yang ada dalam lingkungan tersebut juga rusak dan tidak sehat. Contoh sederhana: jika lingkungan hutan rusak, akibatnya adalah tanah longsor dan banjir, jika lingkungan laut rusak, akibatnya adalah minimnya biotik laut seperti ikan, sehingga para nelayan gagal dalam melaut dan harga ikan meroket. Malahan, kehancuran akibat tsunami juga terpicu oleh kerusakan lingkungan laut, khususnya hutan mangrove. Jika lingkungan tanah rusak, misalnya akibat sampah plastik, akibatnya kesuburan tanah hilang, tanah menjadi tandus.
Dalam ajaran-ajaran agama agung, selalu difatwakan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi dan bumi beserta isinya adalah untuk kepentingan manusia. Bumi dan lingkungan sekitar adalah makhluk ciptaan-Nya untuk kepentingan makhluk yang berpredikat manusia. Selain itu, manusia tidak hanya bertanggung jawab atas kehidupan masa sekarang karena akan memiliki generasi-generasi penerus. Alangkah tragisnya, jika disadari bahwa lingkungan hidup itu akan kita wariskan kepada generasi penerus, anak-cucu kita: lingkungan yang sudah rusak. Lingkungan yang rusak juga akan mengakibatkan generasi yang rusak. Generasi-generasi itu kelak menyesalkan nenek-moyangnya karena tidak mampu mengemban amanah-Nya untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan hidup.
Konteks 2: Santapan Pahit Keseharian: Kesemrawutan Lalu-Lintas

Pemandangan tak sedap terkait dengan kemacetan lalu-lintas hampir rutin dijumpai setiap saat di kota-kota di Indonesia, kota besar maupun kecil, termasuk di Kota Padang. Pada waktu jam-jam sibuk, misalnya pagi sekitar pukul 07.00 dan sore sekitar pukul 17.00, kemacetan lalu-lintas semakin parah. Bukan hanya membuat kesal para pengguna jalan, namun juga sangat merugikan: rugi waktu karena tidak dapat tepat waktu di tempat tujuan seperti sekolah, kantor, rumah maupun rugi BBM. Dampak lain, tingkat emosional para korban kemacetan lalu-lintas juga akan meningkat. Akibat paling parah, korban kecelakaan lalu-lintas semakin meningkat.
Tentu saja, banyak perspektif yang harus digunakan untuk mengurai penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. Salah satu perspektif yang hampir selalu digunakan adalah: ketidakseimbangan pertambahan fasilitas seperti ruas jalan dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Namun, yang jelas, kita pedomani ungkapan bijak, “Jika ingin melihat ketertiban masyarakat suatu kawasan, cermatilah kondisi lalu-lintasnya”. Nah, berarti, kesemrawutan lalu-lintas sangat terkait dengan “kesemrawutan” masyarakat, baik dalam pola berpikir, bersikap, maupun bertindak. Terkait dengan pola berpikir, harus diyakini bahwa jalan-jalan, pasar, taman, dan tempat-tempat umum adalah milik bersama, untuk kepentingan bersama serta harus dipelihara bersama-sama pula. Untuk memanfaatkan hal-hal tersebut, harus dipatuhi rambu-rambu lalu-lintas. Ungkapan “hukum/peraturan itu dibuat untuk dilanggar” adalah ungkapan jahiliyah, tidak bertanggung jawab, dan egois. Terkait dengan pola bertindak, harus diyakini bahwa tindakan kita ketika memanfaatkan jalan dan fasilitas-fasilitas tersebut hendaknya sesuai dengan aturan berlalu-lintas, tidak merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. Terkait dengan pola bersikap, harus kita tanamkan bahwa aturan itu tetap aturan, tanpa pengecualian. Ungkapan bijak, “lamak di awak, katuju dek urang” (enak sama kita, menyenangkan bagi orang lain) hendaknya dijadikan pedoman pengembangan kesadaran memanfaatkan fasilitas berlalu-lintas.
Secara langsung maupun tidak, kesadaran berlalu-lintas adalah kesadaran tekstual. Lalu lintas adalah sebuah teks. Rambu-rambu lalu-lintas serta etika berlalu lintas adalah pola pikir yang dibangun oleh banyak hal di antaranya oleh hasil pembelajaran bahasa berbasis teks. Jadi, jika ada pengendara-pengendara bermotor yang melanggar rambu- rambu seperti tetap menerobos lampu lalu-lintas (traffic light) ketika berwarna merah, tidak menerapkan standar kelengkapan berkendaraan, dan sebagainya itu merupakan bukti ketidakberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia karena mereka tidak menguasai dan menerapkan nilai-nilai pembelajaran tentang teks berlalu-lintas.
Contoh-contoh konteks tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantik mahasiswa/siswa menulis teks-teks bergenre opini. Teks-teks tersebut adalah: teks diskusi, eksposisi, tanggapan, esai, iklan, slogan, poster, deskripsi, persuasi, proposal penelitian, proposal kegiatan, karya ilmiah, dan ceramah. Untuk memicu pemroduksian teks-teks opini tertentu diperlukan tambahan konteks (misalnya ceramah dan pidato): di mana, kapan (misalnya dalam rangka upacara HUT RI), kedudukan penulis (misalnya penulis ditempatkan sebagai kepala sekolah, pejabat kepemerintahan, dan sebagainya), apa tujuannya, siapa khalayaknya (sasaran atau audiens). Konteks-konteks tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memantik siswa menulis teks-teks bergenre sastra puitis (puisi, pantun, syair, dan gurindam) dan bergenre cerita (seperti cerpen, anekdot, eksemplum, dan sebagainya) serta bergenre drama (naskah lakon dan main peran).
Hal lain yang perlu dicermati untuk memanfaatkan konteks adalah rambu-rambu yang jelas. Sebagai contoh, guru menginstruksikan atau menuliskan rambu-rambu: tulislah teks eksposisi dengan judul yang tepat serta mudah dipahami, teks minimal terdiri atas 4 paragraf, dan satu paragraf minimal 3 kalimat. Aspek-aspek yang akan dinilai hendaknya juga dikomunikasikan. Misalnya: aspek-aspek yang dinilai adalah ketepatan judul, struktur, isi, penerapan EYD, dan diksi. Untuk teks-teks puitis, dosen/guru dapat memberikan rambu-rambu yang sesuai: puisi minimal terdiri atas 12 baris, pantun, syair, atau gurindam minimal terdiri atas 4 bait. Tentunya, aspek-aspek penilaian yang digunakan juga berbeda: majas, citraan, rima, metafora, dan sebagainya. Selain itu, selama peserta didik melakukan aktivitas memproduksi atau menulis teks, pendidik harus tegas dalam menegakkan aturan agar peserta didik tidak diperkenankan mengaktifkan gawai.
Dua konteks yang ditampilkan tidak dapat dimanfaatkan sebagai pemicu aktivitas memproduksi teks faktual. Yang dimaksudkan teks-teks faktual adalah teks yang memerlukan data dalam penyusunannya sebab teks-teks tersebut memang difungsikan untuk mengungkapkan fakta. Sebagai contoh, sehebat apa pun, tidak mungkin seorang wartawan berita mampu memproduksi berita jika tidak ada data tentang siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang akan diberitakan. Sepintar apa pun, tidak mungkin seorang penulis mampu membuat teks biografi jika tidak ada data yang layak tentang tokoh yang ditulisnya. Jadi, sangat tidak masuk akal jika dosen/guru menugasi mahasiswa/siswa, misalnya “Tulislah biografi tentang tokoh terkenal di Indonesia”. Sangat aneh, jika dosen/guru menugasi mahasiswa/siswa, “Tulislah berita tentang bencana alam.” Dapat dipastikan, mahasiswa/ siswa akan memanfaatkan internet atau bahkan AI untuk memproduksi teks biografi dan berita karena mahasiswa/siswa tidak dihadapkan atau tidak memiliki data yang cukup untuk memproduksi teks tersebut.
Pascawacana
Perumusan konteks untuk memantik aktivitas mahasiswa/siswa memproduksi teks (berbicara, menulis, atau menyaji) itu sangat penting. Bagi mahasiswa/siswa, konteks akan dimanfaatkan untuk mengakumulasikan segala pengalaman dan pikirannya tentang sesuatu yang relevan dengan pengalaman hidupnya, relevan dengan situasi kekinian. Selanjutnya, mahasiswa/siswa dapat merancang teks yang akan diproduksinya, mengumpulkan bahan, membuat draf, finalisasi, akhirnya mengomunikasikan teks yang diproduksinya.
Untuk kepentingan tes memahami teks dosen/guru akan diuntungkan jika memiliki bank soal, Bank konteks juga sangat fungsional bagi dosen/guru untuk kepentingan pelaksanaan tes keterampilan memproduksi teks. Dari sisi kewacanaan, konteks adalah wacana. Bagi dosen/guru, bank konteks kelak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, misalnya penulisan teks seperti artikel populer, esai, teks-teks cerita, bahkan puitis (puisi, syair, pantun, dan gurindam).
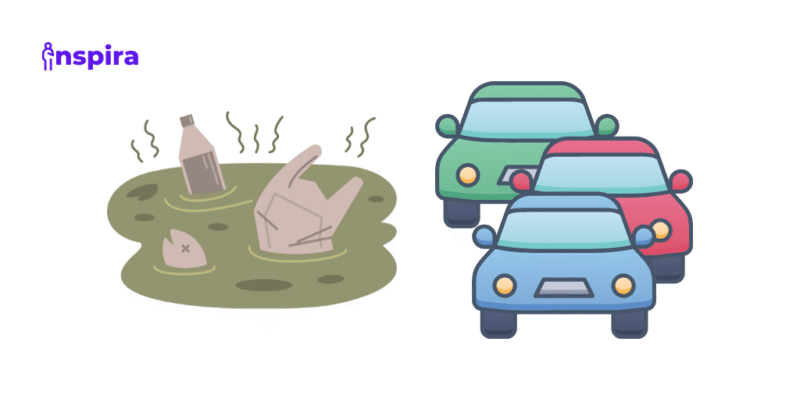
6 comments
Dalam Artikel ini kita tahu bahwa teks-teks nonfaktual adalah teks-teks subgenre opini, cerita, puitis, dan drama dan keuntungan pakai konteks, pada artikel juga dijelaskan yaitu untuk kita lebih Peduli masalah disekitar kita ,tau tugas nya apa dan arahannya kemana dan memicu proses pikir yang aktif.
Dalam artikel ini memberikan pengetahuan yang luas dan berkaitan dengan semantik (makna). Selain itu, teks nonfaktual merupakan teks-teks subgenre opini, cerita, puitis, dan drama.
Dalam artikel ini dijelaskan bahwa teks non-faktual adalah teks yang berisi opini, cerita, puitis dan drama. Informasi yang didasarkan pada subjektif, opini, atau emosi. Jadi teks non-faktual itu sejauh mana kita dapat mengolah informasi jadi tulisan yang dapat memengaruhi emosi dan argumen dari tulisan tersebut.
Dari artikel cara memantik tulisan non faktual dari artikel ini kita dapat mengetahui cara memakai tema tunggal dalam mengajar. Artikel ini kita dapat ketahui makin pendek instruksi nya makin banyak artinya (ambigu) terlalu luas makna nya, kalau tema kuras tepat kita dapat memberi situasi atau gambar yang lebih tepat tentang situasi tersebut.Artikel ini juga memberi tau keuntungan kita memakai konteks.
Dari sisi kewacanaan, konteks adalah wacana. Bagi dosen/guru, bank konteks kelak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain, misalnya penulisan teks seperti artikel populer, esai, teks-teks cerita, bahkan puitis (puisi, syair, pantun, dan gurindam).
Teks ini memberikan argumen kuat bahwa konteks sangat penting dalam pembelajaran menulis. Penjelasan mengenai hubungan konteks, berpikir, dan bahasa membuat pembaca memahami peran guru sebagai fasilitator. Contoh konkret tentang tema umum menunjukkan pentingnya konteks untuk merangsang imajinasi siswa. Pembaca melihat konteks sebagai fondasi untuk menulis dengan relevansi dan pemahaman. Namun, teks ini menuntut guru untuk menyesuaikan paradigma pembelajaran mereka. Guru yang terbiasa memberi tema singkat mungkin perlu panduan lebih tentang merancang konteks yang efektif. Penekanan pada proses berpikir dan pengalaman autentik membuat pembelajaran menulis lebih mendalam.