Banyak pendapat umum (common sense) yang berkembang bahwa membaca merupakan keterampilan berbahasa pasif. Ternyata, pandangan seperti itu tidaklah benar. Membaca bukan sekadar aktivitas melafalkan kata atau kalimat, melainkan proses berpikir yang kompleks. Pembaca membangun makna dari teks melalui interaksi antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan informasi baru yang diperoleh dari bacaan. Jadi, dalam menyusun pemahaman ada interaksi aktif, antara informasi berian (given information) yang merupakan isi teks dengan pengetahuan awal yang dimiliki pembaca. Proses tersebut ada enam tahap, yaitu sebagai berikut ini.
Pertama, pengenalan simbol tulisan. Bahasa yang utama adalah bahasa lisan. Bahasa tulis merupakan representasi bahasa lisan. Representasi tersebut dinamakan ortografi. Dalam Bahasa Indonesia, panduan ortografinya adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang dilengkapi dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI). Oleh karena itu, proses paling awal dalam membaca adalah mengenali simbol tulisan, baik berupa huruf, angka, maupun tanda baca. Pengenalan simbol ini memungkinkan pembaca mengembangkan fonem dan grafem: rangkaian lambang bunyi menjadi suku kata dan akhirnya kata.
Kedua, pencocokan informasi dengan pengetahuan awal. Berdasarkan hasil pengenalan simbol hingga tataran grafem dan kata, pembaca mengaitkan pemahaman tersebut dengan pengetahuan awal yang dimiliki. Jadi, semacam proses dialektika internal. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pengetahuan awal pembaca akan menentukan hasil dialektika tersebut. Pada saat itu, informasi baru (dari teks) dicocokkan dengan skemata yang sudah ada. Misalnya, ketika mengenali judul teks “gempa bumi”, pembaca akan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, pengetahuan geografi, atau berita serupa yang pernah diketahui.
Ketiga, penyusunan makna pada tataran kalimat dan paragraf. Setelah mengenali kata dan struktur kalimat, pembaca mulai menyusun makna pada tingkat yang lebih besar, yaitu koherensi lokal atau hubungan antarkalimat dalam satu paragraf. Pada proses selanjutnya, pembaca menyusun pemahaman pada tataran koherensi global yaitu keterpaduan antarparagraf dalam satu teks utuh. Proses ini membantu pembaca memahami ide pokok, gagasan pendukung, serta alur logis teks.
Keempat, penyusunan inferensi dan elaborasi. Pemahaman tidak hanya berasal dari teks yang eksplisit, tetapi juga dari inferensi (penyimpulan makna yang tersirat). Misalnya, pada teks tertulis “Sungai itu meluap setelah hujan deras semalaman,” pembaca dapat menyimpulkan adanya potensi banjir. Rujukan itu juga dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, misalnya Sungai Citarum Elaborasi terjadi ketika pembaca memperluas makna dengan menghubungkannya pada informasi lain di luar teks.
Kelima, penyusunan evaluasi dan integrasi. Pada tahap ini, pembaca mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tujuannya ada tiga, yaitu (a) mengevaluasi kebenaran, relevansi, dan keterandalan informasi, (b) mengintegrasikan bacaan dengan pengetahuan atau pengalaman baru, dan (c) menyusun simpulan atau sikap tertentu terhadap isi bacaan.
Keenam, penyusunan refleksi dan tindak lanjut yang bersifat aplikatif. Pada tahap ini, pembaca mengembangkan refleksi, yaitu menimbang kembali isi teks dalam hubungannya dengan kehidupan nyata. Hasil refleksi ini dapat diaplikasikan dalam bentuk perubahan sikap, pemecahan masalah, atau lahirnya gagasan baru. Hasil proses terakhir ini kembali disimpan dalam skemata individu yang kelak digunakan lagi ketika pembaca kembali melakukan aktivitas membaca pemahaman.
Deskripsi proses dalam membaca pemahaman, dari proses ke-1 hingga ke-6 membuktikan bahwa membaca itu keterampilan aktif. Dalam menyusun pemahaman, pembaca membutuhkan strategi, konsentrasi, dan keterlibatan penuh secara mental. Pemahaman tidak hanya berhenti pada sekadar mengenali kata, tetapi ke arah evaluasi kritis, integrasi makna, hingga refleksi yang aplikatif. Proses inilah yang menjadikan membaca sebagai sarana penting untuk membentuk individu yang literat, kritis, dan berwawasan luas.
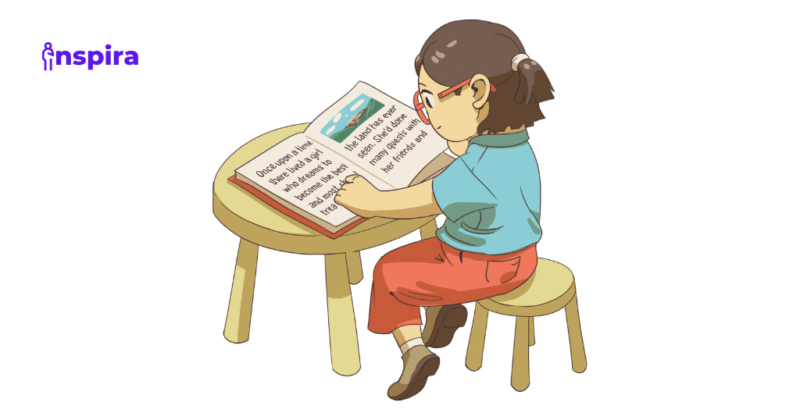
27 comments
Baru sadar ternyata otak kita kerja sekompleks ini setiap kali membaca! Yang sering terlupakan adalah tahap ke-2 dan ke-4—tanpa pengetahuan awal yang memadai, kita cuma ‘membaca’ tapi tidak ‘memahami’. Ini menjelaskan kenapa buku yang sama dibaca oleh dua orang bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda.
Ternyata untuk menyusun ataupun memahami hasil bacaan itu ada beberapa tahapnya dan dengan begitu hasil yang kita baca itu dapat membuat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita lebih mudah memahami makna apa sebenarnya dari teks yang kita baca
Materi penjelasan nya sangat membuka pemahaman saya bahwa proses membaca ternyata bisa sekompleks itu. Saya ikut setuju bahwa membaca itu bukan sekedar menerima secara pasif tetapi menganalisis, menelaah dan mengkaitkan informasi bacaan dengan pemahaman yang sudah diketahui otak.
Teks di atas memberikan pemahaman yang sangat tepat tentang membaca sebagai keterampilan aktif. Saya setuju bahwa membaca tidak hanya sekadar mengenali kata-kata secara pasif, melainkan proses yang kompleks yang melibatkan konsentrasi, strategi, dan keterlibatan mental penuh.
Berarti membaca bukan hanya sekedar membaca sebuah kata atau kalimat melainkan kita harus membaca dengan menggunakan proses agar tidak membaca secara asal-asalan.
Kerangka enam tahap ini berguna sekali untuk mengajar orang agar bisa membaca dengan cerdas. Khususnya, bagian tentang menyimpulkan, menilai, dan menerapkan pengetahuan yang didapat dari teks. Ini mengajarkan bahwa membaca harus membuat kita jadi lebih kritis dan bisa memakai informasi itu untuk kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kita tidak hanya sekadar membaca, tapi juga mengolah informasi agar bisa berguna dan terhubung dengan apa yang kita alami di dunia nyata.
Penjelasan enam tahap proses membaca sebagai aktivitas aktif ini sangat komprehensif, menegaskan bahwa membaca melibatkan interaksi dinamis antara pengetahuan pembaca dan teks, mulai dari pengenalan simbol hingga refleksi aplikatif yang membangun pemahaman mendalam dan kritis. Pendekatan ini selaras dengan strategi membaca aktif modern yang mendorong diskusi, inferensi, dan evaluasi untuk meningkatkan literasi siswa. Penerapannya dalam pendidikan dapat memperkaya pengajaran literatur bagi siswa SMA, sesuai minat Anda sebelumnya
Teks ini menarik karena menjelaskan bahwa membaca merupakan proses aktif yang kompleks, bukan sekadar membaca kata-kata. Penulis memaparkan enam tahap penting dalam menyusun pemahaman, mulai dari pengenalan simbol hingga refleksi dan tindak lanjut aplikatif. Penjelasan yang rinci membuat pembaca memahami bahwa membaca melibatkan interaksi antara informasi baru dan pengetahuan awal. Hal ini menekankan pentingnya strategi, konsentrasi, dan keterlibatan mental saat membaca.Selain itu, teks ini menunjukkan bahwa membaca dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi yang tinggi. Proses evaluasi, integrasi, dan refleksi membantu pembaca menilai kebenaran informasi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan memahami tahap-tahap ini, individu dapat menjadi lebih kritis, kreatif, dan cerdas. Teks ini juga memberikan panduan yang berguna bagi guru maupun siswa dalam meningkatkan kualitas pemahaman membaca.
Saya jadi mengetahui bahwa dalam menyusun pemahaman ada interaksi aktif, antara informasi berian (given information) yang merupakan isi teks dengan pengetahuan awal yang dimiliki pembaca.
Dari teks ini saya sadar bahwa membaca itu ternyata tidak sesederhana yang saya pikir. Selama ini saya hanya fokus pada cara melafalkan kata, tetapi teks ini menjelaskan bahwa membaca membutuhkan proses berpikir. Kita harus benar-benar memahami apa yang dibaca, bukan hanya melihat huruf. Lalu setelah membaca teks ini saya belajar bahwa memahami bacaan membutuhkan latihan, perhatian, dan waktu.
Penjelasan dari teks diatas sangat jelas dan mudah dipahami. Uraiannya menunjukkan bahwa membaca tidak hanya soal mengenali kata, tetapi melibatkan kemampuan berpikir yang aktif. Informasi tentang enam tahap membaca juga membuat pembaca menyadari bahwa pemahaman yang baik membutuhkan latihan dan strategi. Secara keseluruhan, teks ini sangat membantu dalam membuka wawasan bahwa membaca itu adalah keterampilan penting yang membentuk cara berpikir kritis dan mendalam.
Saat membaca penjelasan ini, saya merasakan betapa kompleks dan aktifnya proses membaca sebenarnya. Uraian enam tahapnya sangat jelas dan membuat saya lebih memahami bahwa membaca bukan hanya melafalkan, tetapi aktivitas berpikir yang mendalam. Teks ini membuka wawasan dan mendorong pembaca untuk lebih sadar dalam membangun pemahaman saat membaca.
Teks ini sangat menarik karena menjelaskan bahwa membaca itu aktif dan menuntut berpikir kritis. Saya jadi lebih sadar bahwa membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membangun makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan enam tahap membaca membuat saya memahami betapa kompleksnya proses memahami teks. Ini memotivasi saya untuk lebih fokus dan menggunakan strategi saat membaca agar wawasan semakin luas dan mendalam.
Teks ini sangat informatif, jelas, dan terstruktur dengan baik, sehingga saya sebagai pembaca mudah mengikuti alur pemaparan tentang proses membaca yang aktif. Penjelasan enam tahap membaca mulai dari pengenalan simbol tulisan hingga refleksi dan tindak lanjut memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana membaca melibatkan berpikir kritis, integrasi informasi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata.
Di samping itu, teks ini berhasil menekankan bahwa membaca bukan sekadar mengenali kata atau kalimat, tetapi proses interaksi antara informasi baru dan pengetahuan awal pembaca. Hal ini membuat pembaca mampu mengevaluasi, menyimpulkan, dan mengaplikasikan pemahaman dari teks secara menyeluruh. Penyajian yang runtut dan sistematis menjadikan teks ini bermanfaat bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir kritis.
Teks ini menjelaskan secara rinci enam tahapan aktif dalam proses menyusun pemahaman saat membaca, sekaligus mengoreksi pandangan umum yang keliru bahwa membaca adalah keterampilan pasif. Penulis dengan sistematis menguraikan proses kognitif yang dimulai dari tingkat dasar, yaitu pengenalan simbol tulisan (ortografi), dilanjutkan dengan pencocokan informasi baru dengan pengetahuan awal (skemata), penyusunan makna secara bertahap dari kalimat hingga koherensi global, kemudian berlanjut ke tahap berpikir kritis berupa penyusunan inferensi, elaborasi, evaluasi, integrasi, dan puncaknya adalah refleksi aplikatif yang mengubah sikap atau melahirkan gagasan baru. Penekanan utama teks ini adalah bahwa pemahaman membaca melibatkan interaksi aktif antara teks dan pembaca, menjadikannya proses mental yang kompleks dan esensial dalam membentuk individu yang literat.
Teks eksplanasi tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa membaca bukanlah kegiatan pasif seperti yang sering dianggap orang, tetapi sebenarnya adalah keterampilan aktif yang menuntut proses berpikir mendalam, bukan sekadar mengenali kata. Sebagai pembaca, saya melihat penjelasan yang diberikan runtut dan mudah dipahami, terutama ketika memaparkan enam tahap penting dalam membaca pemahaman, yaitu mengenali simbol tulisan, mencocokkan informasi dengan pengetahuan awal, menyusun makna pada tingkat kalimat dan paragraf, membuat inferensi dan elaborasi, melakukan evaluasi serta integrasi, dan akhirnya melakukan refleksi beserta tindak lanjut. Penjelasan ini membuat saya semakin paham bahwa membaca tidak hanya soal melafalkan kata, tetapi juga membangun makna dan sikap kritis dari setiap informasi yang diterima.
Menurut saya, teks tersebut menjelaskan proses membaca dengan sangat rinci dan membuat kita sadar bahwa membaca itu jauh lebih aktif dari yang selama ini dibayangkan. Penjelasan tahap demi tahap terasa jelas dan masuk akal, terutama ketika menunjukkan bahwa pemahaman terbentuk dari hubungan antara teks dan pengetahuan awal pembaca. Bagian evaluasi dan refleksi juga menarik karena menunjukkan bahwa membaca tidak berhenti pada memahami isi, tetapi sampai pada bagaimana kita menilai dan menerapkannya. Secara keseluruhan, teks ini membantu melihat membaca sebagai aktivitas berpikir yang benar-benar kompleks dan penting.
Ternyata setiap tahap juga dijelaskan dengan contoh yang gampang dibayangkan, jadi saya bisa ngerti gimana otak bekerja saat membaca. Intinya, teks ini nunjukin bahwa membaca adalah kemampuan aktif yang penting untuk menambah pengetahuan dan melatih cara berpikir kritis.
Cerita ini sangat menarik karena membaca bukanlah kegiatan pasif, tetapi sebuah proses yang membuat kita berpikir dan memahami informasi secara aktif. Penjelasannya sangat membantu karena menunjukkan bahwa membaca tidak hanya mengenali huruf dan kata, tetapi juga menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Cerita tersebut juga menekankan bahwa pembaca perlu memahami isi bacaan, menarik kesimpulan, dan menilai apakah informasi itu benar dan bermanfaat. Secara keseluruhan, cerita ini mengingatkan kita bahwa membaca adalah kegiatan penting yang bisa membuat kita lebih cerdas dan mampu berpikir kritis.
Teks ini luar biasa jelas, terstruktur, dan penuh wawasan! Penulis berhasil mengubah persepsi umum tentang membaca dari kegiatan diam menjadi dialog intelektual yang hidup antara pembaca dan dunia.
Membaca bukan hanya sebuah aktivitas biasa, tetapi sebuah keterampilan aktif yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, membaca juga memiliki tahap²an bukan hanya sekedar langsung membaca tampan tahu maknanya
Cerita ini sangat bagus karna menyajikan langkah-langkah dalam proses membaca dengan cara yang jelas dan terstruktur, sehingga membuatnya mudah dimengerti. Diskusi mengenai cara pembaca mengembangkan pemahaman dari tulisan sangat berguna, khususnya untuk meningkatkan keterampilan membaca. Secara umum, teks ini kaya informasi dan penting untuk mendukung kemampuan literasi.
Menurut saya Cerita Teks ini membahas proses kognitif yang terjadi ketika seseorang membaca dan menyusun pemahaman terhadap suatu bacaan.
Saya sepakat dengan pandangan bahwa membaca merupakan keterampilan aktif. Penjelasan enam tahap membaca memperlihatkan bahwa pembaca tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah, menilai, dan mengaitkannya dengan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki. Pemahaman seperti ini penting untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, terutama di tengah arus informasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pembelajaran membaca sebaiknya tidak hanya menekankan kelancaran membaca, tetapi juga strategi memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan isi bacaan agar pembaca menjadi individu yang literat dan berwawasan luas.
Nama ; Axel Dewa Maulana
Nim ; 25137031
Prodi ; S1 Teknik Pertambangan
NU : 05
BI-NS-251
Teks ini adalah panduan pedagogis yang sangat tajam dan logis, secara meyakinkan membuktikan bahwa membaca adalah proses intelektual aktif yang krusial bagi pembentukan karakter kritis dan wawasan luas individu.
Materi penjelasan nya sangat membuka pemahaman saya bahwa proses membaca ternyata bisa sekompleks itu. Ini mengajarkan bahwa membaca harus membuat kita jadi lebih kritis dan bisa memakai informasi itu untuk kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tahap-tahap ini, individu dapat menjadi lebih kritis, kreatif, dan cerdas. Teks ini juga memberikan panduan yang berguna bagi guru maupun siswa dalam meningkatkan kualitas pemahaman membaca.
Nama: Naila Arijta Nadlif
NIM: 25036027
Prodi: Kimia NK
Sesi: 202511280250
Secara keseluruhan, teks ini sangat baik karena bersifat edukatif, menambah wawasan, dan mampu mengubah pandangan pembaca tentang pentingnya membaca secara kritis dan mendalam.