Prawacana
Pada artikel sebelumnya, “Penyajian Konteks untuk Memantik Aktivitas Berbahasa Produktif Teks-Teks Non Faktual” (https://inspiraku.id/penyajian-konteks-untuk-memantik-aktivitas-memproduksi-teks-teks-nonfaktual/) telah dibahas apa rasional, contoh, dan pemanfaatan konteks dalam pembelajaran memproduksi teks-teks nonfaktual (opini, cerita, puitis, dan drama). Rasional dan pemanfaatan konteks untuk memicu aktivitas berbahasa produktif teks-teks faktual dan nonfaktual pada dasarnya sama, yaitu memantik aktivitas berbahasa produktif (berbicara, menulis, dan menyaji) mahasiswa/siswa (selanjutnya disebut peserta didik). Perbedaannya adalah pada rumusan konteksnya. Jadi, konteks “Potret Buram Pencemaran Lingkungan di Indonesia” dan “Santapan Pahit Keseharian: Kesemrawutan Lalu Lintas” tidak dapat dimanfaatkan untuk memantik aktivitas berbahasa produktif teks-teks faktual.
Relevan dengan rasional tersebut, dalam artikel ini dibahas dua hal, yaitu (1) fungsi komunikatif teks-teks faktual dan (2) variasi teks faktual dan konteks yang diperlukan. Variasi teks faktual ada lima, tergantung fakta objek yang hendak diungkapkan. Kemungkinan fakta tersebut adalah objek manusia, nonmanusia, suatu proses, kegiatan, dan peristiwa.
Fungsi Komunikatif Teks-Teks Faktual
Setiap ragam teks memiliki fungsi komunikatif. Justru, dengan adanya keragaman fungsi komunikatif tersebut, berkembanglah konsep genre teks. Artinya, salah satu aspek penting untuk menentukan ragam, jenis, atau genre suatu teks, adalah apa sebenarnya fungsi komunikatif tersebut.
Permasalahan fungsi komunikatif teks merupakan permasalahan dasar yang dibahas dari berbagai sudut pandang keilmuan. Melvil Dewey, misalnya, pada tahun 1876 menciptakan sistem klasifikasi teks yang dikenal dengan istilah Dewey Decimal Classification (lazim disingkat DDC). Dalam DDC teks diklasifikasikan menjadi 10, yaitu (1) 000 – 099 Karya Umum, (2) 100 – 199 Filsafat, (3) 200 – 299 Agama, (4) 300 – 399 Ilmu Sosial, (5) 400 – 399 Bahasa, (6) 500 – 599 Ilmu Murni, (7) 600 – 699 Pengetahuan Praktis, (8) 700 – 799 Kesenian dan Hiburan, (9) 800 – 899 Kesusastraan, dan (10) 900 – 999 Sejarah. Dewey mengklasifikasikan teks berdasarkan isi teks yang dikaitkan dengan bidang keilmuan.
Pengklasifikasian fungsi komunikatif teks yang berujung pada pengklasifikasian genre teks itu ternyata amat variatif. Misalnya, ada yang mengklasifikasikan secara sederhana atas dua: sastra dan nonsastra. Namun, setelah dirunut, kelak juga akan berbuntut panjang. Misalnya, teks sastra akan disubklasifikasikan lagi menjadi puisi, prosa, dan drama. Subklasifikasi puisi akan terbagi lagi menjadi puisi modern dan klasik (pantun, syair, dan gurindam). Sementara, para pakar pembelajaran Bahasa Inggris (misalnya dalam https://literacyideas.com/different-text-types/) mengklasifikasikan teks Bahasa Inggris menjadi 10, yaitu (1) recount atau cerita ulang, (2) response atau tanggapan, (3) narrative atau naratif (cerita), (4) information report atau laporan informasi, (5) poetry atau puisi, (6) procedure atau prosedur, (7) discussion atau diskusi, (8) exposition atau eksposisi, (9) description atau deskripsi, dan (10) explanation atau eksplanasi.
Sebagai pengampu Mata Kuliah Genre Teks Bahasa Indonesia (lazim disingkat GTBI) semenjak tahun 2014, atau semenjak pengimplementasian Kurikulum 2013 (awal perubahan orientasi pembelajaran Bahasa Indonesia dari karangan ke teks) penulis membuat klasifikasi teks atas lima genre. Kelima genre tersebut adalah: (1) opini (atau opini nonsastra), (2) faktual, (3) cerita atau naratif, (4) puitis (dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, teks puitis ini terdiri atas puisi, pantun, syair, dan gurindam), dan (5) drama (termasuk naskah lakon dan main peran). Disadari, pengklasifikasian tersebut bukan tanpa kelemahan. Misalnya, genre opini karena dalam teks sastra pun pengarang atau penyair mungkin saja mengungkapkan opini dalam bentuk puisi, syair, pantun, dan gurindam, atau dalam bentuk cerita seperti cerpen. Perbedaan antara opini dalam teks eksposisi, misalnya, dengan opini dalam teks puisi adalah: opini dalam teks puisi dan teks kesastraan itu bersifat kreatif dan personal sedangkan dalam teks nonsastra bersifat logis. Namun, disadari juga, pengklasifikasian teks bukan hal yang sederhana sekaligus akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan hidup dan kehidupan manusia.
Teks-teks faktual yang dimaksudkan dalam pengklasifikasian genre teks yang penulis buat juga beragam. Keragaman tersebut disebabkan oleh adanya variasi fakta objek. Variasi fakta objek itu ada lima, yaitu: (1) manusia, (2) alam, (3) proses, (4) kegiatan, dan (5) peristiwa. Pada prinsipnya, keragaman teks faktual tersebut mengemban fungsi komunikatif yang identik. Teks faktual dalam bahasa Indonesia adalah teks digunakan untuk yang menyajikan informasi berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi, bukan opini atau pendapat pribadi. Pemroduksi teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca, penyimak, atau pemirsa.
Teks Faktual tentang Objek Manusia dan Konteks yang Diperlukan
Salah satu teks faktual yang objeknya manusia, baik dalam Kurikulum 2013 (selanjutnya disingkat Kurtilas) dan Kurikulum Merdeka (selanjutnya disingkat Kurmer) adalah teks biografi. Dalam contoh, teks biografi selalu berkaitan dengan sosok terkenal, pahlawan, dan sebagainya. Dengan tujuan, pembaca dapat memetik nilai-nilai keteladanan atas kehebatan tokoh tersebut. Tentu saja, dalam konteks pembelajaran memahami, mengidentifikasi, mereproduksi, dan menganalisis teks biografi, hal itu bernilai positif.
Disayangkan, berkembang kecenderungan dosen/guru (selanjutnya disebut pendidik) terbawa arus ketika menugasi peserta didik menulis teks biografi. Lazimnya, pendidik menginstruksi-kan, “Tulislah teks biografi pahlawan yang berasal dari daerah kita”, atau “Tulislah biografi (misalnya) tentang Bung Hatta!” Hal itu jelas aneh. Sebab, untuk menulis, misalnya biografi pahlawan atau tokoh ternama, tentu diperlukan data tentang tokoh tersebut. Dapat dipastikan, peserta didik akan melacak data tokoh dari internet. Apalagi, biografi tentang tokoh terkenal itu tentunya sudah ada di internet pula. Akibat fatal lainnya, peserta didik akan salin-rekat (copy paste), atau memanfaatkan AI untuk mengerjakan tugas menulis biografi tokoh terkenal tersebut. Peserta didik tidak sepenuhnya dapat disalahkan jika melakukan salin-rekat atau memanfaatkan AI dalam mengerjakan tugas menulis biografi sebab pendidik yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan hal itu.
Konteks untuk memicu peserta didik menulis teks biografi sebaiknya bertahap. Pada tahap pertama, pendidik menugasi peserta didik mengumpulkan data tentang tokoh/sosok yang dikagumi, sekaligus dapat dijadikan informan yang dapat diwawancarai dalam rangka pengumpulan data. Misalnya, “Siapa tokoh/sosok yang paling Sdr. kagumi? Boleh, ayah, ibu, anggota keluarga besar, atau orang yang masih hidup dan dapat dijadikan informan! Jika sudah ditemukan, wawancarailah sehingga Sdr. memperoleh data lengkap berkaitan identitas tokoh (nama, tempat/tanggal lahir, alamat, agama, nama ayah, ibu, dan anggota keluarga tokoh tersebut, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, serta hal-hal atau peristiwa yang dianggap istimewa atas sosok/tokoh tersebut!” Untuk mempermudah peserta didik mengerjakan tugas, berilah format-format isian. Tentu saja, tugas pengumpulan data tentang tokoh tersebut dilaksanakan di luar jam PBM.
Tahap kedua adalah penugasan menulis teks biografi. Sebelum itu, pendidik hendaknya memastikan seluruh peserta didik telah mengerjakan tugas (misalnya di Buku Latihan) pengumpulan data tokoh yang dikagumi. Peserta didik yang tidak mengerjakan tugas tersebut tidak boleh disertakan dalam pengerjaan tugas sebab tidak mungkin menulis teks biografi tanpa adanya data. Instruksi tugas hendaknya juga jelas dan tegas, misalnya “Tulislah teks biografi sesuai dengan data yang telah Sdr. kumpulkan. Tulisan hendaknya sesuai dengan struktur, isi, dan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan karakteristik bahasa teks biografi.” Contoh teks biografi dalam Platform Inspira (selanjutnya disingkat PI) adalah “Ilyas Ya’kub: Api Kemerdekaan dari Barat Sumatera” (https://inspiraku.id/ilyas-yakub/).
Teks Faktual tentang Objek Non-Manusia dan Konteks yang Diperlukan
Salah satu teks faktual tentang objek nonmanusia dalam Kurtilas dan Kurmer adalah teks laporan hasil observasi (lazim disingkat LHO). Teks ini dimanfaatkan untuk mengungkapkan fakta tentang objek yang dapat diobservasi, atau dapat diindera, atau menggunakan alat-alat penginderaan seperti teleskop, mikroskop, timbangan, meteran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam buku ajar, lazim ditampilkan teks, misalnya tentang biota laut, hutan, hutan mangrove, pantai, binatang, pohon, buah, bunga, dan sebagainya.
Dalam pembelajaran memahami, mereproduksi, dan menganalisis, tentu saja objek-objek yang beragam itu dapat dijadikan sebagai objek tulisan teks LHO. Namun, untuk memantik peserta didik menulis teks LHO, objek-objek seperti gunung, laut, hutan, pohon, binatang, dan sebagainya tidak mungkin dijadikan sebagai konteks, termasuk video atau gambar tentang objek-objek tersebut. Sebab, intinya, peserta didik harus mampu mengobservasi serta mengumpulkan data tentang objek yang akan ditulisnya. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu menampilkan objek yang dapat diobservasi langsung oleh peserta didik. Sebagai contoh, pendidik membawa dan meletakkan objek-objek di atas meja di depan ruang kelas: tiga jenis sepatu (sport, casual atau santai, dan pantofel). Untuk membantu peserta didik memahami objek, masing-masing sepatu dilengkapi dengan label, misalnya label jenis sepatu, konteks yang tepat untuk memakai sepatu tersebut, dan kisaran harga. Pendidik memperlihatkan satu per satu objek dan membacakan label agar seluruh peserta didik memiliki data yang sama tentang objek-objek tersebut. Sesudah itu, tugasilah peserta didik, misalnya, “Tulislah teks LHO tentang jenis, konteks pemakaian, dan kisaran harga sepatu-sepatu ini. Ingat berilah judul yang tepat, tulisan minimal terdiri atas 4 paragraf, 1 paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Ingat pula, struktur teks LHO selain judul adalah deskripsi umum, serta deskripsi subjek atau bagian. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar!”
Silakan cek Buku Ajar Mapel Bahasa Indonesia tingkat SLTP dan SLTA. Judul-judul teks LHO yang ditampilkan sebagai bahan bacaan adalah judul-judul yang aneh karena terlalu singkat atau pendek. Misalnya, teks LHO berjudul “Hutan Bakau”, atau “Harimau Sumatera”. Judul-judul tersebut tidak menggambarkan secara spesifik apa yang diobservasi. Dalam PI, misalnya, ditampilkan contoh-contoh teks LHO, “Arsitektur, Bagian, dan Denah Umum Rumah Gadang” (https://inspiraku.id/arsitektur-bagian-dan-denah-umum-rumah-gadang/) sehingga pembaca mendapatkan gambaran umum hanya dengan membaca judul teks bahwa yang akan diungkapkan adalah tentang arsitektur, bagian, dan denah umum berkaitan dengan objek yang diobservasi, yaitu rumah gadang. Judul lain, “Ciri Umum, Bagian, dan Manfaat Kelapa bagi Manusia” (https://inspiraku.id/ciri-umum-bagian-dan-manfaat-kelapa-bagi-manusia/) juga menggambarkan spesifikasi objek yang diobservasi.
Teks Faktual tentang Objek suatu Proses dan Konteks yang Diperlukan
Teks faktual juga dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta tentang proses. Proses tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dilakukan oleh manusia (by human) dan bersifat alamiah (by nature). Diksi alamiah merujuk bahwa proses itu terjadi tanpa campur tangan langsung manusia, bukan berarti tentang alam. Sebagai contoh, proses memasak nasi goreng adalah proses by human, sementara proses terjadinya hujan adalah proses by nature. Proses pertumbuhan jerawat adalah proses by nature, sementara proses mengurus surat izin mengemudi (SIM) adalah proses by human. Dalam Kurtilas dan Kurmer, nama teks faktual tentang prosedur by human adalah teks prosedur. Pada awal pengimplementasian Kurtilas, teks prosedur ada dua yaitu teks prosedur sederhana (fakta tentang proses sederhana dan dikerjakan dalam satu satuan waktu, misalnya tentang cara memasak mie goreng) dan teks prosedur kompleks (fakta proses berjenjang yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya cara mengurus dan mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, atau cara mengurus dan memperoleh paspor). Ciri penanda yang paling mudah ditandai adalah judul teks, lazimnya judul diawali dengan diksi Cara, misalnya “Cara Membuat Blog, Cara Memasak Nasi Goreng Istimewa” dan sebagainya. Sementara itu, teks yang dimanfaatkan untuk mengungkapkan fakta tentang proses yang alamiah disebut teks eksplanasi. Lazimnya judul teks eksplanasi diawali dengan diksi Proses, misalnya “Proses Abrasi di Pantai Pesisir Sumatera Barat.”
Pada masa lalu, sebelum maraknya pemanfaatan internet, teks prosedur banyak disajikan dalam bentuk buku, misalnya “Buku Resep Masakan”, dan di media-media massa cetak di koran, misalnya “Cara Memasang Rantai Sepeda”. Pada masa sekarang, teks prosedur sangat mudah ditemukan di media digital (internet, YouTube, TikTok, Instagram) dan sebagainya. Topik yang dibahas juga variatif, dari yang sederhana seperti cara memasak sesuatu, tutorial memakai jilbab, hingga yang kompleks seperti cara membuat blog, memperbaiki kerusakan laptop, hp, dan sebagainya. Kemasan teks prosedur di media digital juga menarik, dilengkapi dengan gambar, bahkan video. Kondisi ini menguntungkan pendidik karena dapat menugasi peserta didik untuk memproduksi teks prosedur dalam bentuk media tulis (menulis) dan media tayang (membuat video). Tentunya, pendidik memiliki pertimbangan tertentu, misalnya ketersedian prasarana, jaringan internet, dan terutama waktu pengerjaan tugas. Untuk menulis teks prosedur, dapat dilakukan di dalam kelas dan waktunya relatif singkat sementara untuk membuat video tidak mungkin dilaksanakan di dalam kelas serta waktunya relatif lama (misalnya seminggu). Meskipun demikian, untuk memantik peserta didik memproduksi teks prosedur, diperlukan konteks yang jelas dan relevan dengan fungsi teks.
Konteks yang diperlukan untuk memantik aktivitas peserta didik memproduksi teks prosedur adalah konteks yang bermuatan: apa yang akan diproduksi, alat dan bahan yang diperlukan, dan gambaran umum prosedur yang harus dikerjakan. Sebagai contoh, pendidik mengomunikasikan, “Tugas Sdr. adalah menulis cara memasak rendang. Untuk memasak rendang, alat-alat yang diperlukan adalah kuali yang berukuran sedang, bahan-bahannya: 1 kg daging sapi, 1 liter santan kental dari 3 butir kelapa (perasan pertama tanpa air), 550 gram kelapa parut, disangrai sampai kecokelatan, 5 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, 10 lembar daun jeruk, 5 batang serai, 1/2 batang kayu manis, 3 butir cengkeh, 2 sdt garam, dan 1 buah kembang lawang. Bumbu-bumbu yang diperlukan: 65 gram bawang putih, 125 gram bawang merah, 15 gram kunyit, 35 gram jahe, 75 gram lengkuas, 35 gram kemiri, 1/2 sdt lada bubuk, 1 sdt ketumbar, 1 buah kapulaga, dan 1/4 buah pala”. Tulislah teks prosedur yang sesuai dengan struktur, dan gunakanlah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.” Dalam praktik kebanyakan, pendidik beranggapan bahwa para peserta didik sudah tahu tentang rendang dan cara memasaknya sehingga memberikan instruksi singkat, “Tulislah teks prosedur tentang cara memasak rendang.” Padahal, meskipun lokasi sekolah berada di Padang dan peserta didik dipastikan memahami kuliner Sumatera Barat, belum mereka memahami secara rinci, misalnya bumbu-bumbu yang diperlukan. Pada kenyataannya, peserta didik pasti akan melacak tentang memasak rendang di internet. Dengan konteks yang jelas seperti dicontohkan tadi, pendidik hendaknya menginstruksikan agar peserta didik menonaktifkan gawai selama proses menulis teks prosedur berlangsung. Contoh teks prosedur dalam PI adalah “Memanfaatkan Hyphothes.is untuk Kolaborasi Pembelajaran di Inspira” (https://inspiraku.id/cara-menggunakan-hypothesis-di-inspira/).
Seperti sudah digambarkan sebelumnya, teks faktual yang dimanfaatkan untuk mengungkapkan proses yang bersifat alamiah adalah teks eksplanasi. Sesuai dengan karakteristik “proses alamiah”, tentu saja proses yang diungkapkan itu berlangsung relatif lama, tidak seperti dalam teks prosedur. Misalnya, proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, proses terjadinya tsunami, proses perkembangan permukiman kumuh di suatu kawasan, proses fotosintesis, proses pencernaan makanan, dan sebagainya. Intinya, tidak mungkin pendidik menugasi peserta didik untuk mengamat-amati proses tersebut sehingga memperoleh data yang cukup sebagai bahan penulisan teks eksplanasi. Untuk itu, penyajian konteks pemicu pemroduksian teks eksplanasi dilakukan melalui tiga cara.
Cara pertama adalah dengan menggunakan media gambar. Sesuai dengan konsep “proses”, selayaknya gambar yang digunakan adalah gambar berseri. Misalnya, untuk menyajikan konteks proses terjadinya hujan, pendidik menayangkan media gambar berseri: gambar pertama tentang penguapan atau evaporasi, gambar kedua tentang pengembunan atau kondensasi, gambar ketiga tentang pembentukan awan, dan gambar keempat tentang mulai turunnya hujan (presipitasi). Pendidik hendaknya memastikan bahwa seluruh peserta didik memahami informasi proses yang ada dalam gambar, jika perlu menugasi peserta didik mencatat poin-poin penting proses tersebut.
Cara kedua adalah dengan menayangkan video, misalnya proses terjadinya gerhana bulan. Sangat mudah menemukan video-video seperti itu, misalnya di YouTube. Pendidik menayangkan video dan menginstruksikan agar peserta didik mencatat poin-poin penting tentang proses terjadinya hujan. Setelah itu, pendidik menugasi peserta didik menulis teks eksplanasi tentang proses terjadinya gerhana bulan.
Cara ketiga adalah cara yang paling praktis, tidak memerlukan media kecuali tulisan. Dengan pemahaman teks eksplanasi itu mengungkapkan data sehingga menjadi fakta tentang proses yang bersifat alamiah, pendidik mengomunikasikan rangkaian proses tersebut. Misalnya, pendidik menulis dan membagikannya kepada siswa, “Hujan merupakan proses alamiah yang termasuk fenomena alam. Proses tersebut ada 4 tahap: (1) penguapan atau evaporasi, (2) pengembunan atau kondensasi, (3) pembentukan awan, dan (4) akhirnya turun hujan. Tulislah teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan. Ingat, struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Tulisan tersebut minimal terdiri atas 6 paragraf, 1 paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Pergunakanlah Bahasa Indonesia yang baik dan benar!”
Sama halnya dengan penugasan pemroduksian teks lainnya, ketika peserta didik melakukan aktivitas menulis pendidik hendaknya menegaskan aturan agar tidak mengaktifkan gawai. Hal ini dilakukan agar tidak berkembang kemungkinan adanya kecurangan, misalnya menyalin dari Google atau memanfaatkan aplikasi berbasis AI. Di pihak lain, jika peserta didik tidak menerima konteks yang jelas, tentu tidak mungkin mampu menulis teks eksplanasi. Jadi, instruksi “Tulislah eksplanasi tentang proses terjadinya hujan” adalah instruksi yang tidak tepat. Sehebat apa pun seorang penulis, tanpa adanya data tidak akan mampu menulis teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi di PI adalah “Proses Terjadinya Jerawat: (https://inspiraku.id/proses-terjadinya-jerawat/).
Teks Faktual tentang Objek suatu Peristiwa dan Konteks yang Diperlukan
Variasi teks faktual lainnya adalah teks berita. Secara umum, berita diproduksi untuk mengungkapkan fakta tentang suatu peristiwa yang luar biasa dan menyangkut hidup serta kehidupan manusia. Jadi, objeknya adalah fakta tentang peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, janggal jika pendidik memberikan instruksi singkat kepada peserta didik untuk menulis teks berita hanya dengan, “Tulislah berita tentang bencana alam! Tulislah berita tentang banjir!” dan sebagainya. Sebab, sehebat apa pun, tidak mungkin seorang wartawan dapat menulis berita tanpa ada data tentang fakta atas peristiwa tersebut. Akibatnya, mudah ditebak. Peserta didik akan salin-rekat berita yang ada di internet, atau memanfaatkan AI.
Data yang diperlukan untuk menulis teks berita dikenal dengan unsur berita, yaitu apa, (what), siapa (who), kapan, (when), di mana (where), mengapa (why), dan bagaimana (how), dikenal dengan 5W+1H atau akronim adiksimba. Oleh sebab itu, konteks pemicu menulis berita yang diperlukan juga hendaknya data tentang enam unsur tersebut. Misalnya, “Ada kebakaran rumah di Jl. Prof. Dr. Hamka, No 56 Air Tawar, Kota Padang. Satu rumah terbakar habis, satu rumah terbakar sekitar 30%. Korban: meninggal 1 orang (Udin, umur 62 tahun, pemilik rumah yang terbakar habis), 2 orang mengalami luka bakar cukup parah (Tuti, 55 tahun, istri Udin, dan Bujang, 30 tahun, anak pasangan Udin-Tuti). Menurut saksi mata, tetangga korban, Ahmad (57 tahun) pijar api pertama terlihat pada pukul 23.50 WIB, 25 Agustus 2025, dari ruang dapur. Menurut Kapolsek Padang Utara, AKP Bagus Bana, M.H. api diduga berasal dari hubungan arus pendek (korsleting). Dinas Kebakaran Kota Padang mengerahkan 4 unit mobil damkar. Api berhasil dipadamkan pada pukul 04.15 dinihari. Korban dirawat di RSUP M Djamil Padang. Kerugian ditaksir 650 juta rupiah”.
Setelah menyajikan konteks, pendidik memberikan tugas, misalnya “Tulislah berita lengkap sesuai dengan konteks tersebut. Sdr. diberi peluang untuk menambahkan data namun harus relevan dengan data utama yang ada dalam konteks. Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ragam bahasa jurnalistik. Waktu untuk menulis, 60 menit!” Dengan demikian, tidak akan ditemukan teks berita karya peserta didik yang aneh, misalnya “Kebakaran di Wilayah Cibinong”, “Banjir Bandang di Daerah Bogor”. Aneh, sebab lokasi sekolah peserta didik di Padang. Contoh teks berita di PI adalah “Warganya Gunakan Pukat Harimau di Perairan Sumbar, Walikota Sibolga Datangi Wagub Vasco Minta Maaf” (https://inspiraku.id/wali-kota-sibolga-temui-wagub-vasco-karena-pukat-harimau/)
Teks Faktual tentang Objek suatu Kegiatan dan Konteks yang Diperlukan
Variasi teks faktual lainnya adalah teks laporan tentang suatu kegiatan. Kegiatan itu berbeda dengan peristiwa, sebab kegiatan merupakan sesuatu yang direncanakan sementara peristiwa adalah sesuatu yang tidak direncanakan, bahkan mungkin tidak terduga. Selain itu, pembelajaran tentang teks laporan kegiatan jelas memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran teks yang lain. Sebab, ada dua langkah: melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sesudah itu baru melaporkannya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan, kegiatan itu sendiri tentunya dilaksanakan di luar kelas, bahkan di luar jam pembelajaran. Itulah sebabnya, mungkin, alasan penyusun Kurmer untuk Mapel Bahasa Indonesia di tingkat SLTA menghilangkan nama-nama teks laporan (laporan perjalanan, laporan kegiatan), kecuali LHO. Untuk tingkat SLTP, masih ada teks faktual tentang kegiatan yang diberi label “Teks Laporan Percobaan.”
Teks laporan percobaan bukanlah teks faktual murni. Sebab, di dalam teks tersebut ada teks LHO (ketika mendeskripsikan alat dan bahan yang diperlukan), ada teks prosedur (ketika mendeskripsikan proses percobaan), ada teks eksposisi (ketika membahas hasil percobaan). Teks-teks yang multigenre lazim disebut sebagai teks hibridis. Konteks ideal untuk memicu aktivitas memproduksi (misalnya menulis) teks laporan percobaan adalah video. Sangat mudah untuk menemukan video tersebut, misalnya di YouTube, tentang percobaan. Pada saat mencermati video, peserta didik diberi tugas mencatat poin-poin penting, yang mencakup apa alat dan bahan yang diperlukan, bagaimana prosedur pelaksanaan percobaan, dan apa hasil serta penjelasan tentang hasil percobaan tersebut.
Selain teks percobaan, sebenarnya ada teks-teks lain yang dapat dibelajarkan untuk memahami dan memproduksi teks faktual tentang laporan kegiatan. Misalnya, teks laporan bacaan dan teks laporan wawancara. Namun, karena dalam Kurmer Mapel Bahasa Indonesia SMP dan SMA tidak disajikan dalam esai ini. Contoh teks faktual laporan kegiatan dalam PI adalah teks laporan wawancara “Mengenal Lebih Dekat Sosok Pelajar Berprestasi Dunia: Model 1 dan Model 2” (https://inspiraku.id/mengenal-lebih-dekat-sosok-pelajar-berprestasi-dunia/).
Pascawacana
Konteks untuk memicu aktivitas peserta didik memproduksi (lazimnya, menulis) teks-teks faktual itu sangat penting. Tidak mungkin, tanpa adanya data pendukung fakta yang akan dilaporkan, peserta didik akan mampu menulis teks tersebut. Sesuai dengan jenis fakta yang hendak diungkapkan (tentang objek nonmanusia, manusia, proses, peristiwa, dan kegiatan), konteks harus mengungkapkan data yang layak.
Hal lain yang perlu dicermati dalam pembelajaran memproduksi teks, apa pun teksnya, adalah kebijakan yang hendaknya dipatuhi peserta didik agar menonaktifkan gawai selama proses menulis. Untuk itu, pendidik juga meyakinkan bahwa dalam pembelajaran menulis, yang lebih penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Melalui proses yang baik, tentu hasilnya juga akan baik. Selain itu, lebih ideal lagi jika tulisan peserta didik dibahas secara umum, mungkin berkaitan dengan judul, struktur, isi, dan penggunaan bahasanya. Setelah itu, peserta didik diberi tugas merevisi tulisannya. Boleh saja, merevisi itu dilakukan di luar jam pembelajaran. Selanjutnya, pendidik menugasi peserta didik untuk menyerahkan tulisannya, yang belum dan sudah direvisi. Merevisi tulisan sendiri merupakan pembelajaran yang sangat bermakna.
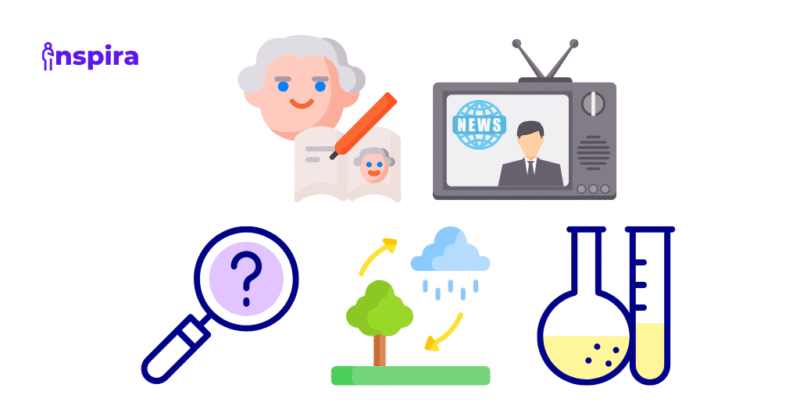
10 comments
Kita dapat mengetahui bahwa teks faktual adalah data yang berisi fakta bukan opini, dan memiliki 5 objek yaitu non manusia , manusia, proses, peristiwa,dan kegiatan dan dalam penulisannya ketika kita ingin menulis biografi tokok pahlawan misalnya maka kita harus tau apa saja datanya terlebih dahulu
Dari artikel ini kita dapat mengetahui teks faktual itu teks yang isi nya fakta yang memberi informasi yang akurat,teks faktual ini di bagi berdasarkan objeknya manusia , nonton manusia, proses, peristiwa, dan kegiatan dari artikel ini kita ambil contoh yang objek manusia saat kita membuat biografi kita harus tau data dari tokoh yang akan kita buat biografinya jadi kita ambil aja tokoh yang dekat sama kita seperti keluarga dan guru yang bisa kita wawancara.
Teks faktual yang objeknya manusia salah satu contohnya adalah teks biografi. Teks biografi merupakan teks yang disajikan berupa fakta, tidak bisa di karang-karang sendiri. Tujuan dari kita mempelajari teks biografi yaitu memetik nilai-nilai keteladanan atau kehebatan tokoh-tokoh tersebut.
Masya Allah ilmu baru, ternyata sepenting itu bekal ilmu yang cukup untuk siswa sebelum kita sebagai pendidik memberi instruksi kepada siswa tersebut
Dalam artikel ini menambah wawasan kita tentang tentang teks biografi (manusia), teks LHO , teks prosedur (proses), teks eksplanasi, teks berita (fakta peristiwa), dan lainnya. Ini sangat membantu kita dalam mengajar peserta didik bagaimana teks yang baik.
penjelasan mengenai teks biografi, teks LHO, teks prosedur, dan teks lainnya memberikan pemahaman rinci mengenai bagaimana sebuah teks digunakan dalam pembelajaran belajar mengajar.
Artikel ini sangat informatif dan praktis! Penulis berhasil menjelaskan dengan sangat jelas perbedaan konteks yang diperlukan untuk memantik produksi teks faktual dibandingkan teks nonfaktual. Poin utamanya kuat: guru harus menyediakan data dan konteks yang spesifik agar siswa dapat menulis berdasarkan fakta, bukan sekadar menyalin dari internet atau AI.
Dalam teks di atas menjelaskan tentang biografi manusia, teks LHO, teks prosedur, dan lain lain. ini sangat mengajar kan kita gimana teks yang baik.
Nurzikri_25016149 NU : 09
SIMAK-NS-025
teks ini juga mengingatkan bahwa pembelajaran membaca bukan tugas sekolah saja, tetapi tugas bersama—keluarga, guru, dan lingkungan. Ada kelembutan yang tersirat ketika membahas pentingnya peran orang tua yang membacakan cerita, menciptakan suasana yang hangat, dan memberi waktu bagi anak untuk mengenal huruf dengan cara yang menyenangkan. Dari sini tampak bahwa membaca tidak boleh dipaksakan sebagai kewajiban, melainkan ditumbuhkan sebagai kebiasaan yang penuh kedekatan dan rasa.
Cerita ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang pentingnya dalam menulis berbagai jenis teks faktual. Penulis menjelaskan yang memebuat kita akan lebih mudah menulis dengan benar jika kita mendapatkan data yang jelas, bukan hanya diminta menulis tanpa informasi. Saya setuju bahwa banyak tugas menulis di sekolah sering membuat siswa kebingungan karena tidak diberi contoh atau konteks yang tepat. Penjelasan dalam cerita ini bermanfaat karena menunjukkan cara yang lebih baik untuk membimbing kita agar tidak hanya menyalin dari internet. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih bermakna dan kita benar-benar memahami apa yang kita tulis.